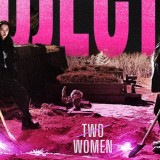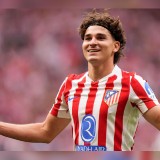TIMES PONOROGO, PONOROGO – Saat ini isu dualisme pengaturan desa kembali mencuat ke permukaan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola pemerintahan desa. Sejak disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi desa secara hukum telah mengalami transformasi signifikan.
Desa kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak asal-usul, kewenangan lokal, dan ruang otonomi dalam mengatur rumah tangganya sendiri.
Dalam praktiknya, desa sering kali terjebak dalam tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, yang menimbulkan fenomena dualisme pengaturan desa.
Salah satu bentuk paling nyata dari dualisme ini adalah keberadaan dua entitas hukum yang diakui oleh UU Desa, yakni desa administratif dan desa adat. Desa administratif berfungsi sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional yang berorientasi pada pelayanan publik, sementara desa adat merupakan satuan masyarakat hukum yang berakar pada tradisi, kearifan lokal, dan struktur sosial budaya yang khas.
Kedua bentuk desa ini idealnya bisa berjalan berdampingan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, pada praktiknya, pengakuan terhadap desa adat sering kali bersifat formalitas belaka.
Banyak pemerintah daerah yang belum memiliki peraturan daerah untuk menegaskan eksistensi dan batas kewenangan desa adat. Akibatnya, desa adat kerap terpinggirkan, kehilangan ruang kulturalnya, dan dipaksa menyesuaikan diri dengan struktur administratif yang seragam.
Dualisme ini menciptakan ketegangan antara otonomi kultural dan otonomi administratif. Padahal, semangat UU Desa justru mendorong pengakuan terhadap keberagaman, bukan penyeragaman.
Selain soal bentuk kelembagaan, dualisme pengaturan desa juga tampak dalam tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Kemendagri mengatur desa dari aspek pemerintahan dan kelembagaan, sementara Kemendes PDTT berwenang dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Secara ideal, kedua kementerian ini harus bersinergi. Namun dalam praktiknya, koordinasi sering kali lemah dan tumpang tindih kebijakan tidak terhindarkan.
Fakta paling nyata terlihat dalam pengelolaan Dana Desa. Meski bersumber dari APBN dan disalurkan melalui Kemendes PDTT, pertanggungjawabannya harus mengikuti mekanisme administrasi yang diatur oleh Kemendagri.
Di lapangan, perangkat desa sering kali kebingungan menghadapi dua sistem pengawasan dan pelaporan yang berbeda. Belum lagi intervensi pemerintah kabupaten yang juga berkepentingan. Akibatnya, bukan efisiensi yang tercipta, melainkan birokrasi berlapis yang justru memperlambat pelayanan dan membuka ruang bagi praktik maladministrasi.
Dualisme pengaturan desa juga tidak bisa dilepaskan dari dimensi politik. Pemerintah desa kini menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara aktor lokal dan nasional. Kepala desa sering dihadapkan pada dilema antara loyalitas kepada masyarakatnya atau kepatuhan terhadap regulasi dan instruksi pemerintah di atasnya.
Kehadiran dana desa yang besar rata-rata lebih dari Rp 1 miliar per desa per tahun menambah daya tarik politik desa. Banyak kebijakan nasional bersifat top-down, menjadikan desa sekadar pelaksana program tanpa ruang partisipasi yang berarti.
Desa seolah diposisikan sebagai kepanjangan tangan birokrasi, bukan sebagai entitas otonom yang berdaya. Kondisi ini tentu melahirkan situasi dilematis. Di satu sisi desa diberi kewenangan luas, namun di sisi lain tetap dikontrol secara ketat melalui berbagai regulasi dan instrumen administratif.
Mengurai dualisme pengaturan desa memerlukan pendekatan yang sistematis dan politis sekaligus kultural. Setidaknya terdapat tiga langkah strategis yang perlu dipertimbangkan untuk mengurai problem dualisme tersebut.
Pertama, perlu dilakukan sinkronisasi regulasi antar kementerian yang terkait dengan desa. UU Desa memang sudah menjadi payung hukum utama, namun banyak aturan turunannya justru saling tumpang tindih.
Misalnya, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD dan Permendes Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa, yang sering kali menimbulkan perbedaan tafsir dalam praktik. Pemerintah perlu membentuk satu badan koordinasi lintas kementerian yang memastikan keselarasan regulasi dan implementasi kebijakan desa.
Kedua, perlu dilakukan penguatan kapasitas pemerintahan desa agar mampu memahami dan menavigasi kerumitan regulasi yang ada. Pelatihan dan pendampingan hukum harus difokuskan bukan hanya pada administrasi, tetapi juga pada tata kelola partisipatif dan akuntabilitas sosial.
Ketiga, negara harus memberikan pengakuan yang lebih substansial terhadap desa adat. Pengakuan tidak boleh berhenti pada simbolisme hukum, tetapi harus diwujudkan dalam perlindungan terhadap hak ulayat, struktur kepemimpinan adat, serta sistem hukum lokal yang hidup di masyarakat.
Dualisme pengaturan desa mencerminkan persoalan klasik dalam demokrasi Indonesia: antara otonomi dan kontrol, antara keberagaman dan penyeragaman. Negara perlu bergeser dari paradigma pengawasan menuju paradigma kemitraan dengan desa. Negara harus bersedia berbagi kekuasaan dengan komunitas di tingkat bawahnya, yakni desa.
Jika negara bersedia berbagi kekuasaan secara tulus, maka desa dapat menjadi laboratorium demokrasi partisipatif yang sejati. Sebagaimana dikatakan oleh Elinor Ostrom (1990) dalam teorinya tentang governing the commons, bahwa komunitas lokal memiliki kapasitas untuk mengatur dirinya sendiri bila diberikan kepercayaan dan dukungan kelembagaan yang memadai.
Untuk mengakhiri dualisme pengaturan desa bukan sekadar persoalan administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat demokrasi dari akar rumput.
***
*) Oleh : Lukman Santoso Az, bergiat di ICMI dan MUI Ponorogo, Juga Dosen Fakultas Syariah UIN Ponorogo.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |