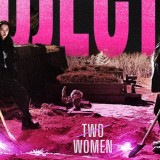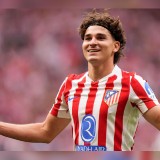TIMES PONOROGO, PONOROGO – Ponorogo kembali menjadi sorotan dunia. Setelah seni Reog diakui UNESCO sebagai Intangible Cultural Heritage (Warisan Budaya Takbenda) pada Desember 2023, kini kabupaten di ujung barat Jawa Timur itu resmi masuk dalam UNESCO Creative Cities Network (UCCN) kategori Crafts and Folk Art.
Penetapan ini diumumkan melalui laman resmi unesco.org pada 31 Oktober 2025, menempatkan Ponorogo sejajar dengan 408 kota kreatif dunia. Dengan dua pengakuan internasional sekaligus untuk warisan tradisi dan ekosistem kreatifnya, Ponorogo kini menjadi salah satu simbol keberhasilan daerah yang mampu menumbuhkan kreativitas dari akar budaya lokal.
Capaian ini bukanlah dari hasil kerja instan. Ini merupakan prestasi dari semua elemen masyarakat Ponorogo. Penetapan UCCN merupakan buah dari perjalanan panjang membangun ekosistem budaya yang hidup dan berkelanjutan.
Reog bukan hanya tarian seremonial, melainkan sumber inspirasi bagi lahirnya industri kreatif yang resilien dan berdaya saing global. Dari seni pertunjukan hingga kriya dan kerajinan tangan, semuanya tumbuh di atas fondasi nilai, spiritualitas, dan tradisi yang kokoh.
Data pemerintah daerah menunjukkan, ekosistem Reog melibatkan lebih dari 23.840 pelaku seni dengan perputaran ekonomi mencapai Rp150 miliar per tahun. Sementara sektor kriya yang meliputi produksi dadak merak, topeng Bujangganong, kostum, dan perangkat gamelan, melibatkan 273 pelaku usaha kecil dengan omzet sekitar Rp6,4 miliar per tahun.
Angka ini membuktikan bahwa pelestarian budaya tidak hanya menghasilkan kebanggaan simbolik, tetapi juga manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.
Namun, setelah gemuruh tepuk tangan penghargaan UNESCO mereda, pertanyaan yang lebih substansial muncul: ke mana arah kebijakan Ponorogo pasca penetapan UNESCO? Pengakuan global ini seharusnya tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola kebudayaan dan ekonomi kreatif yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif.
Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa negara berkewajiban memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Dengan demikian, status Reog sebagai Warisan Budaya Takbenda dan Ponorogo sebagai Kota Kreatif UNESCO bukan hanya kehormatan, tetapi juga mandat konstitusional untuk menjaga, melindungi, dan mengembangkan kebudayaan.
Sayangnya, orkestrasi kebijakan pelestarian budaya sering kali berhenti pada tataran simbolik. Setelah pengakuan UNESCO, fokus kebijakan kerap diarahkan pada pembangunan monumen atau kegiatan seremonial, bukan pada penguatan kapasitas pelaku budaya dan kelembagaan. Padahal, salah satu syarat utama pengakuan UNESCO adalah adanya rencana pelestarian yang konkret dan berkelanjutan.
Dalam kerangka policy paradigm yang dikemukakan Peter Hall (1993), kebijakan publik harus mampu menggeser orientasi pemerintah dari sekadar administrasi menuju respons terhadap tantangan sosial dan kultural. Ponorogo perlu melakukan lompatan paradigma serupa: dari “kebanggaan budaya” menuju “pembangunan berbasis budaya.”
Pertama, penguatan pendidikan budaya lokal. Reog perlu diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah Ponorogo dan sekitarnya.
Tujuannya bukan sekadar melestarikan tarian, tetapi mentransmisikan nilai-nilai kepahlawanan, kepemimpinan, dan gotong royong yang terkandung di dalamnya. Regenerasi pelaku budaya hanya mungkin terjadi jika pengetahuan budaya diwariskan sejak dini.
Kedua, perlindungan sosial dan ekonomi bagi pelaku seni. Ribuan seniman, penari, dalang, warok, hingga pengrajin adalah garda terdepan pelestarian.
Pemerintah daerah perlu menyiapkan skema insentif mulai dari dana kesenian, asuransi budaya, hingga penghargaan rutin bagi pelaku budaya yang berkontribusi menjaga tradisi. Investasi pada manusia budaya jauh lebih penting daripada sekadar infrastruktur seremonial.
Ketiga, pembentukan lembaga khusus pelestarian dan diplomasi budaya Reog. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas sektor: antara pemerintah, komunitas Reog, akademisi, UMKM kreatif, dan mitra internasional.
Selain mengurusi riset, sertifikasi, dan digitalisasi arsip budaya, lembaga ini juga bisa menjadi motor diplomasi budaya Ponorogo di kancah global.
Keempat, penguatan perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional. Meski Reog sudah diakui UNESCO, Indonesia tetap harus aktif mengamankan hak kekayaan intelektual komunal agar tidak diklaim pihak lain. Perlindungan hukum bukan hanya simbol kedaulatan, melainkan benteng terhadap komersialisasi yang menyalahi nilai budaya.
Kelima, integrasi Reog dalam pariwisata kreatif yang beretika. Komersialisasi tidak boleh menghapus makna sakral dan filosofi Reog. Pemerintah perlu membuat regulasi tegas agar pertunjukan wisata tetap menghormati pakem tradisionalnya. Kolaborasi dengan sektor pariwisata sebaiknya diarahkan pada format edukatif mengangkat nilai, bukan sekadar tontonan.
Masuknya Ponorogo ke dalam jejaring UCCN membuka peluang besar untuk knowledge sharing, cultural diplomacy, dan investasi berbasis budaya. Namun peluang ini hanya bisa dioptimalkan bila pemerintah daerah memiliki peta jalan kebudayaan yang jelas. Peta ini harus menghubungkan antara pendidikan, ekonomi kreatif, riset budaya, dan pariwisata secara terpadu.
Dengan dukungan UNESCO, Ponorogo bisa memperluas kerja sama internasional dalam bentuk festival budaya, pertukaran seniman, hingga pengembangan pusat kreatif regional. Jejaring ini juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pasar global bagi produk kriya lokal dan pertunjukan Reog.
Namun, kunci keberhasilan tetap pada gotong royong masyarakat budaya. Pemerintah daerah memang menjadi pemimpin orkestra, tetapi nada harmoni hanya akan muncul jika komunitas, sekolah, pelaku UMKM, dan tokoh adat ikut memainkan perannya.
Oleh karena itu, pelestarian Reyog harus didekati dengan semangat gotong royong berbasis meaningfull participation. Komunitas Reyog, pemuda, sekolah, tokoh adat, hingga pelaku UMKM harus dilibatkan dalam proses ini. Karena bagaimanapun, dalam negara hukum seperti Indonesia, tugas utama pelestarian warisan budaya tetap harus dipimpin oleh negara.
Bukan dalam arti otoritarianisme budaya, melainkan kepemimpinan yang berpihak pada nilai, pelaku, dan keberlanjutan. Orkestrasi kebijakan pelestarian Reyog pasca-UNESCO harus bersifat kolaboratif, terstruktur, dan berkelanjutan.
Akhirnya, pengakuan dunia adalah kehormatan, tetapi menjaga keasliannya adalah tanggung jawab besar. Jika dikelola dengan visi jangka panjang, Ponorogo bisa menjadi model kota yang menumbuhkan kesejahteraan dari kebudayaan.
Reog tidak hanya ditampilkan, tetapi juga ditumbuhkan. Tidak sekadar dikagumi, tetapi juga dilindungi. Karena sejatinya, kehormatan dari dunia baru berarti bila diiringi tanggung jawab untuk menjaganya dengan berkeadilan dan berkeadaban.
***
*) Oleh : Lukman Santoso Az, bergiat di ICMI dan MUI Ponorogo, Juga Dosen Fakultas Syariah UIN Ponorogo.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |